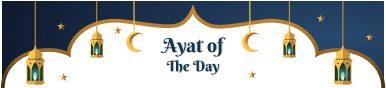Definisi Ayat yang Dinilai Qath'iy Al-Dalalah, Begini Pejelasan Quraish Shihab
Sabtu, 24 Agustus 2024 - 06:08 WIB
Prof Quraish Shihab. Foto/Ilustrasi: Ist
Apakah yang dinamai qath'iy dan apa atau bagaimana proses yang dilaluinya sehingga suatu ayat dinilai qath'iy al-dalalah? Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan qath'iy al-dalalah: "Yang menunjuk kepada makna tertentu yang harus dipahami darinya (teks); tidak mengandung kemungkinan takwil serta tidak ada tempat atau peluang untuk memahami makna selain makna tersebut darinya (teks tersebut)."
Prof Dr Quraish Shihab dalam bukunya berjudul "Membumikan al-Qur'an, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat" (Mizan, 1996) menyebut definisi serupa dikemukakan juga oleh Syaikh Abu Al-'Ainain Badran Abu Al-'Ainain: "Sesuatu yang menunjuk kepada hukum dan tidak mengandung kemungkinan (makna) selainnya."
Sementara itu, Al-Syathibi, dalam Al-Muwafaqat, menulis demikian: "Tidak atau jarang sekali ada sesuatu yang pasti dalam dalil-dalil syara' yang sesuai dengan penggunaan (istilah) yang populer."
Yang dimaksudkan adalah istilah yang dinukil di atas, atau yang semakna dengannya seperti dijelaskan oleh 'Ali 'Abdul Wahhab. Mereka merumuskan "definisi populer" tersebut dengan "tidak adanya kemungkinan untuk memahami dari suatu lafal kecuali maknanya yang dasar itu."
"Tidak atau jarang sekali ada sesuatu yang pasti dalam dalil-dalil syara'", (jika berdiri sendiri) ini, menurut Al-Syathibi, karena apabila dalil-dalil syara' tersebut bersifat ahad, maka jelas ia tidak dapat memberi kepastian.
Bukankah ahad sifatnya zhanniy? Sedangkan bila dalil tersebut bersifat mutawatir lafalnya, maka untuk menarik makna yang pasti dibutuhkan premis-premis (muqaddimat) yang tentunya harus bersifat pasti (qath'iy) pula.
Menurut Quraish, dalam hal ini, premis-premis tersebut harus bersifat mutawatir. Ini tidak mudah ditemukan, karena kenyataan membuktikan bahwa premis-premis tersebut semuanya atau sebagian besarnya bersifat ahad dalam arti zhanniy (tidak pasti). "Sesuatu yang bersandar kepada zhanniy, tentu tidak menghasilkan sesuatu kecuali yang zhanniy pula," katanya.
Muqaddimat yang dimaksud Al-Syathibi di atas adalah apa yang dikenal dengan al-ihtimalat al-'asyrah, yakni: (1) riwayat-riwayat kebahasaan; (2) riwayat-riwayat yang berkaitan dengan gramatika (nahw); (3) riwayat-riwayat yang berkaitan dengan perubahan kata (sharaf); (4) redaksi yang dimaksud bukan kata bertimbal (ambigu, musytarak); atau (5) redaksi yang dimaksud bukan kata metaforis (majaz); (6) tidak mengandung peralihan makna; atau (7) sisipan (idhmar); atau (8) "pendahuluan dan pengakhiran" (taqdim wa ta'khir); atau (9) pembatalan hukum (naskh); dan (10) tidak mengandung penolakan yang logis (adam al-mu'aridh al-'aqliy).
Tiga yang pertama bersifat zhanniy, karena riwayat-riwayat yang menyangkut hal-hal tersebut semuanya ahad. Tujuh sisanya hanya dapat diketahui melalui al-istiqra' al-tam (metode induktif yang sempurna), dan hal ini mustahil.
Menurut Quraish, yang dapat dilakukan hanyalah al-istiqra' al-naqish (metode induktif yang tidak sempurna), dan ini tidak menghasilkan kepastian. Dengan kata lain, yang dihasilkan adalah sesuatu yang bersifat zhanniy.
Prof Dr Quraish Shihab dalam bukunya berjudul "Membumikan al-Qur'an, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat" (Mizan, 1996) menyebut definisi serupa dikemukakan juga oleh Syaikh Abu Al-'Ainain Badran Abu Al-'Ainain: "Sesuatu yang menunjuk kepada hukum dan tidak mengandung kemungkinan (makna) selainnya."
Sementara itu, Al-Syathibi, dalam Al-Muwafaqat, menulis demikian: "Tidak atau jarang sekali ada sesuatu yang pasti dalam dalil-dalil syara' yang sesuai dengan penggunaan (istilah) yang populer."
Yang dimaksudkan adalah istilah yang dinukil di atas, atau yang semakna dengannya seperti dijelaskan oleh 'Ali 'Abdul Wahhab. Mereka merumuskan "definisi populer" tersebut dengan "tidak adanya kemungkinan untuk memahami dari suatu lafal kecuali maknanya yang dasar itu."
"Tidak atau jarang sekali ada sesuatu yang pasti dalam dalil-dalil syara'", (jika berdiri sendiri) ini, menurut Al-Syathibi, karena apabila dalil-dalil syara' tersebut bersifat ahad, maka jelas ia tidak dapat memberi kepastian.
Bukankah ahad sifatnya zhanniy? Sedangkan bila dalil tersebut bersifat mutawatir lafalnya, maka untuk menarik makna yang pasti dibutuhkan premis-premis (muqaddimat) yang tentunya harus bersifat pasti (qath'iy) pula.
Menurut Quraish, dalam hal ini, premis-premis tersebut harus bersifat mutawatir. Ini tidak mudah ditemukan, karena kenyataan membuktikan bahwa premis-premis tersebut semuanya atau sebagian besarnya bersifat ahad dalam arti zhanniy (tidak pasti). "Sesuatu yang bersandar kepada zhanniy, tentu tidak menghasilkan sesuatu kecuali yang zhanniy pula," katanya.
Muqaddimat yang dimaksud Al-Syathibi di atas adalah apa yang dikenal dengan al-ihtimalat al-'asyrah, yakni: (1) riwayat-riwayat kebahasaan; (2) riwayat-riwayat yang berkaitan dengan gramatika (nahw); (3) riwayat-riwayat yang berkaitan dengan perubahan kata (sharaf); (4) redaksi yang dimaksud bukan kata bertimbal (ambigu, musytarak); atau (5) redaksi yang dimaksud bukan kata metaforis (majaz); (6) tidak mengandung peralihan makna; atau (7) sisipan (idhmar); atau (8) "pendahuluan dan pengakhiran" (taqdim wa ta'khir); atau (9) pembatalan hukum (naskh); dan (10) tidak mengandung penolakan yang logis (adam al-mu'aridh al-'aqliy).
Tiga yang pertama bersifat zhanniy, karena riwayat-riwayat yang menyangkut hal-hal tersebut semuanya ahad. Tujuh sisanya hanya dapat diketahui melalui al-istiqra' al-tam (metode induktif yang sempurna), dan hal ini mustahil.
Menurut Quraish, yang dapat dilakukan hanyalah al-istiqra' al-naqish (metode induktif yang tidak sempurna), dan ini tidak menghasilkan kepastian. Dengan kata lain, yang dihasilkan adalah sesuatu yang bersifat zhanniy.
(mhy)
Lihat Juga :