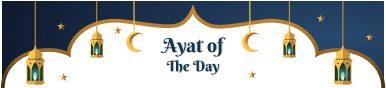Kisah Tabi'in Ar-Rabi bin Khutsaim dan Nasihatnya yang Menyentuh Hati
Minggu, 15 Desember 2024 - 16:01 WIB
Ibnu Masud merasakan ketulusan dan keikhlasan ar-Rabi. IlustrasI; AI
Ar-Rabi bin Khutsaim adalah salah satu ulama tabiin yang utama dan satu di antara delapan orang yang dikenal paling zuhud di masanya. Beliau adalah murid dari Abdullah bin Mas'ud, sahabat Rasulullah SAW .
Kecintaan guru terhadap muridnya laksana kasih sayang seorang ibu terhadap anak tunggalnya. Ar-Rabi biasa keluar masuk rumah gurunya tanpa harus meminta izin. Bila dia datang, maka yang lain tidak diizinkan masuk sebelum ar-Rabi keluar.
Dr Abdurrahman Ra'fat Basya dalam "Mereka adalah Para Tabiin" menyebut beliau adalah orang Arab asli, suku Mudhar dan silsilahnya bertemu dengan Rasulullah SAW pada kakeknya, Ilyas dan Mudhar.
Ibnu Mas'ud merasakan ketulusan dan keikhlasan ar-Rabi. Kebagusan ibadahnya yang memancar kuat di hatinya, rasa kecewanya lantaran tertinggal dari zaman Nabi, sehingga tidak mendapat kesempatan untuk menjadi salah satu sahabat beliau.
"Tidakkah sebaiknya kuantarkan engkau kepada syaikh agar kita bisa menambah keimanan sesaat?" ajak Hilal bin Isaf kepada tamunya yang bernama Mundzir ats-Tsauri, suatu ketika. Syaikh yang dimaksud adalah Syaikh Ar-Rabi bin Khutsaim.
"Baik, aku setuju," jawab Mundzir antusias. "Demi Allah, tiada yang mendorong aku datang ke Kufah ini melainkan karena ingin bertemu dengan gurumu, Rabi bin Khutsaim dan rindu untuk bisa tinggal sesaat dalam taman iman bersamanya. Akan tetapi apakah engkau sudah minta izin kepadanya? Kudengar dia menderita penyakit rematik sehingga tidak keluar rumah dan enggan menerima tamu?"
"Memang begitulah orang-orang Kufah mengenalnya, sakitnya itu tidak mengubahnya barang sedikit pun," ujar Hilal.
"Baiklah. Tetapi Anda tahu bahwa syaikh ini memiliki perasaan yang halus, apakah menurut Anda kita layak mendahului bicara dan bertanya sesuka kita? Atau kita diam saja menunggu beliau mulai bicara?" tanya Mundzir ragu.
"Andaikata engkau duduk bersama Rabi bin Khutsaim selama setahun lamanya, maka dia tidak akan bicara apapun kecuali jika engkau yang mulai berbicara dan akan terus diam bila tidak kau dahului dengan pertanyaan. Sebab dia menjadikan ucapannya sebagai zikir dan diamnya untuk berpirkir," jelas Hilal.
"Kalau begitu, marilah kita mendatanginya dengan barakah Allah Subhanahu wa Taala," ajak Mundzir setuju.
Kemudian pergilah mereka berkedua ke rumah syaikh itu. Setelah memberi salam, mereka bertanya, "Bagaimana kabar Anda pagi ini wahai syaikh?"
"Dalam keadaan lemah, penuh dosa, memakan rezeki-Nya, dan menanti ajalnya," jawab Ar-Rabi.
"Sekarang di Kufah ini ada tabib yang handal. Apakah syaikh mengizinkan kami memanggilnya untuk Anda?" ujar Hilal.
"Wahai Hilal, aku tahu bahwa obat itu adalah benar-benar berkhasiat. Tetapi aku belajar dari kaum Aad, Tsamud, penduduk Rass dan abad-abad di antara mereka. Telah kudapati bahwa mereka sangat gandrung dengan dunia, rakus dengan segala perhiasannya. Keadaan mereka lebih kuat dan lebih ahli dari kita. Di tengah-tengah mereka banyak tabib, namun tetap saja ada yang sakit. Akhirnya tak tersisa lagi yang mengobati maupun yang diobati karena binasa," jawab Ar-Rabi. Beliau kemudian menghela nafas panjang dan berkata, "seandainya itulah penyakitnya, tentulah aku akan berobat."
"Kalau demikian, apa penyakit yang Anda derita wahai Syaikh?" tanya Mundzir.
"Penyakitnya adalah dosa-dosa," jawabnya.
"Lantas, apa obatnya?" tanya Mundzir lagi.
"Obatnya adalah istighfar," jawab Ar-Rabi.
Kecintaan guru terhadap muridnya laksana kasih sayang seorang ibu terhadap anak tunggalnya. Ar-Rabi biasa keluar masuk rumah gurunya tanpa harus meminta izin. Bila dia datang, maka yang lain tidak diizinkan masuk sebelum ar-Rabi keluar.
Dr Abdurrahman Ra'fat Basya dalam "Mereka adalah Para Tabiin" menyebut beliau adalah orang Arab asli, suku Mudhar dan silsilahnya bertemu dengan Rasulullah SAW pada kakeknya, Ilyas dan Mudhar.
Ibnu Mas'ud merasakan ketulusan dan keikhlasan ar-Rabi. Kebagusan ibadahnya yang memancar kuat di hatinya, rasa kecewanya lantaran tertinggal dari zaman Nabi, sehingga tidak mendapat kesempatan untuk menjadi salah satu sahabat beliau.
"Tidakkah sebaiknya kuantarkan engkau kepada syaikh agar kita bisa menambah keimanan sesaat?" ajak Hilal bin Isaf kepada tamunya yang bernama Mundzir ats-Tsauri, suatu ketika. Syaikh yang dimaksud adalah Syaikh Ar-Rabi bin Khutsaim.
"Baik, aku setuju," jawab Mundzir antusias. "Demi Allah, tiada yang mendorong aku datang ke Kufah ini melainkan karena ingin bertemu dengan gurumu, Rabi bin Khutsaim dan rindu untuk bisa tinggal sesaat dalam taman iman bersamanya. Akan tetapi apakah engkau sudah minta izin kepadanya? Kudengar dia menderita penyakit rematik sehingga tidak keluar rumah dan enggan menerima tamu?"
"Memang begitulah orang-orang Kufah mengenalnya, sakitnya itu tidak mengubahnya barang sedikit pun," ujar Hilal.
"Baiklah. Tetapi Anda tahu bahwa syaikh ini memiliki perasaan yang halus, apakah menurut Anda kita layak mendahului bicara dan bertanya sesuka kita? Atau kita diam saja menunggu beliau mulai bicara?" tanya Mundzir ragu.
"Andaikata engkau duduk bersama Rabi bin Khutsaim selama setahun lamanya, maka dia tidak akan bicara apapun kecuali jika engkau yang mulai berbicara dan akan terus diam bila tidak kau dahului dengan pertanyaan. Sebab dia menjadikan ucapannya sebagai zikir dan diamnya untuk berpirkir," jelas Hilal.
"Kalau begitu, marilah kita mendatanginya dengan barakah Allah Subhanahu wa Taala," ajak Mundzir setuju.
Kemudian pergilah mereka berkedua ke rumah syaikh itu. Setelah memberi salam, mereka bertanya, "Bagaimana kabar Anda pagi ini wahai syaikh?"
"Dalam keadaan lemah, penuh dosa, memakan rezeki-Nya, dan menanti ajalnya," jawab Ar-Rabi.
"Sekarang di Kufah ini ada tabib yang handal. Apakah syaikh mengizinkan kami memanggilnya untuk Anda?" ujar Hilal.
"Wahai Hilal, aku tahu bahwa obat itu adalah benar-benar berkhasiat. Tetapi aku belajar dari kaum Aad, Tsamud, penduduk Rass dan abad-abad di antara mereka. Telah kudapati bahwa mereka sangat gandrung dengan dunia, rakus dengan segala perhiasannya. Keadaan mereka lebih kuat dan lebih ahli dari kita. Di tengah-tengah mereka banyak tabib, namun tetap saja ada yang sakit. Akhirnya tak tersisa lagi yang mengobati maupun yang diobati karena binasa," jawab Ar-Rabi. Beliau kemudian menghela nafas panjang dan berkata, "seandainya itulah penyakitnya, tentulah aku akan berobat."
"Kalau demikian, apa penyakit yang Anda derita wahai Syaikh?" tanya Mundzir.
"Penyakitnya adalah dosa-dosa," jawabnya.
"Lantas, apa obatnya?" tanya Mundzir lagi.
"Obatnya adalah istighfar," jawab Ar-Rabi.
Lihat Juga :