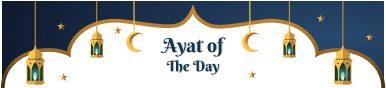Genosida Israel: Kisah Ahed Bseiso Diamputasi, Menahan Sakit dengan Membaca Al-Quran
Jum'at, 02 Februari 2024 - 13:56 WIB
Ahed Bseiso setelah diamputasi. Foto: al Jazzera
Ahed Bseiso mengalami disorientasi, terkejut, dan mati rasa terhadap rasa sakit luar biasa setelah dia terluka akibat penembakan Israel di rumah keluarganya di Gaza utara.
“Yang saya lihat hanyalah kabut putih… Sesaat, saya pikir saya sudah mati,” kata Ahed kepada Al Jazeera, mengenang peristiwa 19 Desember.
Hari itu, mengikuti rutinitasnya sejak 7 Oktober, ketika Israel melancarkan serangan paling brutal di Gaza hingga saat ini, mahasiswi berusia 17 tahun dan kakak perempuannya, Mona, naik ke lantai enam gedung mereka pada pukul 10.30.
Mereka pergi ke sana untuk menelepon ayah mereka, yang tinggal di luar negeri. Mereka mencoba berbicara dengannya setiap hari untuk memberitahunya bahwa mereka masih hidup di tengah pengepungan, pemboman hebat, dan kekurangan pasokan penting.
Pemadaman telekomunikasi dan kemacetan yang berulang di Gaza membuat banyak orang harus naik ke atap untuk mendapatkan sinyal, mencari penguat sinyal, atau menggunakan kartu eSIM yang terhubung ke operator telekomunikasi regional mana pun.
Ahed mengatakan dia melihat sebuah tank Israel berukuran luar biasa besar di luar gedung, tapi dia tidak terlalu memikirkannya karena rumah mereka telah dikelilingi oleh kendaraan tentara setelah gencatan senjata antara Israel dan Hamas berakhir pada bulan November.
Dia duduk dan bersiap untuk menghubungi nomor ayahnya.
"Saya berhasil mengatakan 'Saya hidup'. “Saya menyilangkan kaki dan tiba-tiba, saya terbalik,” katanya.
Ahed kehilangan salah satu anggota tubuhnya – hampir seluruh betis kanannya – dan mengeluarkan banyak darah.
Keterkejutannya sangat parah sehingga dia terdiam, begitu pula saudara perempuannya – dia kemudian menyadari “Mona takut memanggilku kalau-kalau aku tidak menjawab”.
“Akhirnya, ketika saya memahami apa yang baru saja terjadi, saya berhasil mengatakan: ‘Saya hidup’.”
Sepupu laki-laki Ahed bergegas menggendongnya ke bawah. Dia ingat melihat ke bawah dan berteriak, bertanya kepada sepupunya apakah kakinya masih di sana karena dia tidak dapat melihatnya.
“Yang dilakukan sepupu saya hanyalah menutup mata,” kenangnya.
Satu-satunya tempat mereka bisa mendudukkan Ahed adalah di meja makan, tempat ibunya tadi sedang menguleni adonan roti, pemandangan umum di rumah-rumah di Gaza ketika pengepungan total Israel membuat makanan dan bahan pokok menjadi langka.
Seseorang berlari mencari pamannya, Hani, seorang ahli ortopedi dan satu-satunya dokter di antara 30 kerabat yang tinggal di gedung keluarga.
Hani telah mengirim istri dan empat anaknya keluar dari daerah kantong pada awal serangan, sementara dia tetap tinggal.
Maka, dia mendapati dirinya memandangi kaki keponakannya yang terputus dan mengetahui bahwa dia harus menyelamatkannya, tanpa persediaan medis, anestesi, atau bahkan kain kasa bersih.
Di Gaza saat ini, petugas medis harus melakukan prosedur tanpa bantuan apa pun, bahkan tanpa alat untuk mengendalikan rasa sakit, sebagai akibat dari kekurangan tenaga medis akibat pengepungan tersebut.
Hani harus mengambil pilihan yang sulit namun jelas: mengamputasi sisa kaki bagian bawah dan segera menjahit arteri agar keponakannya tidak mati kehabisan darah.
“Saya tidak punya apa-apa. Saya ingat tas kerja saya ada di kamar, jadi saya minta keponakan saya untuk mengambilnya… Tidak ada apa-apa di sana kecuali kain kasa yang tidak steril,” kata Hani.
Hani tidak tahu bagaimana cara membersihkan luka atau mengendalikan pendarahan, sebuah tugas yang tampaknya mustahil tanpa jahitan.
Sementara itu, fasilitas medis terbesar di Gaza, Rumah Sakit al-Shifa, berjarak “lima menit perjalanan dengan mobil” namun tidak dapat dijangkau dan tidak dapat digunakan karena pertempuran tersebut, kata Hani.
Seperti kebanyakan rumah sakit di wilayah kantong tersebut, al-Shifa telah diserang dan digerebek pada bulan November, memaksa ribuan warga Palestina yang terluka dan terlantar di sana untuk melarikan diri dan membuat rumah sakit tersebut tidak dapat berfungsi lagi.
Hani melihat sekeliling ruangan dengan putus asa, mencari apa pun untuk membuat proses mengerikan itu lebih mudah ditangani. Di wastafel dapur, dia melihat spons dan wadah berisi sabun cuci piring.
“Saya mulai membersihkan lukanya tetapi merasakan mata Ahed menusuk saya. Dia memohon agar saya tidak memotong sisa kakinya,” kata Hani.
Hatinya hancur dan air mata membasahi wajahnya, mengetahui apa yang harus ia lakukan selagi Ahed sadar sepenuhnya.
“Saya bertanya-tanya orang mana yang bisa menanggung sakitnya amputasi tanpa anestesi,” kata Hani.
Maka dia mengoperasi keponakannya dengan pisau dapur dan menggunakan jarum dan benang dari peralatan menjahit untuk menjahit arteri terbesar.
Ketika ditanya bagaimana dia mampu menahan rasa sakit, Ahed mengatakan perasaan tenang yang aneh mengambil alih.
“Saya hanya membaca ayat-ayat Al-Quran sepanjang waktu,” katanya.
Untuk memperbaiki lukanya, keluarga tersebut harus mencuci kain kasa tersebut dengan air panas dan menjemurnya hingga kering sehingga pamannya dapat memasangkannya kembali ke kakinya.
Mengetahui Ahed rentan terhadap infeksi, Hani mengatakan bahwa dia meminum “semua pil antibiotik dan obat penghilang rasa sakit yang ada di rumah,” dan membagikannya kepada Ahed, kebanyakan saat perut kosong karena tidak ada makanan.
Baru lima hari kemudian Hani dapat memindahkannya ke fasilitas medis – satu hari setelah tank Israel mundur dari daerah tersebut. Di sana, Ahed menjalani beberapa operasi, termasuk salah satunya untuk memperbaiki kaki kirinya yang patah.
Tapi itu masih belum cukup, kata Hani.
“Dia membutuhkan lebih banyak lagi… operasi perbaikan kosmetik untuk kakinya yang diamputasi, sebuah anggota tubuh palsu,” kata Hani.
“Saya bisa saja pergi bersama istri dan anak-anak saya, tapi Tuhan membiarkan saya tetap tinggal. Aku tinggal di sini agar Ahed bisa hidup.”
Ahed adalah salah satu generasi muda yang diamputasi yang muncul dari daerah kantong tersebut akibat serangan Israel yang tiada henti.
Menurut Dana Anak-Anak PBB, lebih dari 10 anak kehilangan satu atau kedua kaki mereka setiap hari di Gaza sejak 7 Oktober. Itu berarti lebih dari 1.000 anak.
Praktik Standar
Para profesional medis mengatakan banyak dari mereka yang tewas di Gaza sejak 7 Oktober sebenarnya bisa diselamatkan jika mereka bisa mencapai rumah sakit.
Abed, seorang dokter ortopedi dari Doctors Without Borders – juga dikenal sebagai Medecins Sans Frontieres (MSF) – mengatakan petugas medis di Gaza bergantung pada obat penenang pasien di tengah kurangnya anestesi.
“Kami kekurangan semua jenis obat,” kata Abed, yang selama ini bekerja di Rumah Sakit Lapangan Indonesia Rafah dan meminta agar hanya nama depannya yang disebutkan karena alasan keamanan.
“Kami bergantung pada obat pereda nyeri seperti parasetamol dan kami mencoba anestesi lokal untuk mengurangi rasa sakit,” katanya.
Menurut Abed, pasien menjalani “ amputasi traumatis ” setiap hari, dan sebagian besar pasien adalah anak-anak.
Ketika sebuah rumah sakit menampung banyak orang yang terluka, diperlukan waktu berjam-jam bagi seseorang untuk sampai ke ruang operasi, sehingga penyelamatan anggota tubuh menjadi tidak mungkin dan amputasi diperlukan “untuk menyelamatkan nyawa pasien”, katanya.
Menurut Kementerian Kesehatan di Gaza, Israel telah menewaskan hampir 27.000 orang dan melukai sekitar 65.000 lainnya dalam serangannya di Gaza sejak 7 Oktober. Hampir seperempat korban cedera terjadi pada anak-anak, kata kementerian tersebut.
Ahed mengatakan dia selamanya berubah. Sebelum penyerangan, dia terdaftar untuk belajar farmasi. Tapi sekarang dia tidak tahan “apapun yang berhubungan dengan obat-obatan” karena apa yang telah dia alami.
“Saya akan mengubah jurusan saya,” katanya. “Saya akan menjadi seorang desainer interior dan membuktikan kepada dunia bahwa saya masih bisa menjalani kehidupan normal meskipun saya memiliki cacat fisik.”
“Yang saya lihat hanyalah kabut putih… Sesaat, saya pikir saya sudah mati,” kata Ahed kepada Al Jazeera, mengenang peristiwa 19 Desember.
Hari itu, mengikuti rutinitasnya sejak 7 Oktober, ketika Israel melancarkan serangan paling brutal di Gaza hingga saat ini, mahasiswi berusia 17 tahun dan kakak perempuannya, Mona, naik ke lantai enam gedung mereka pada pukul 10.30.
Mereka pergi ke sana untuk menelepon ayah mereka, yang tinggal di luar negeri. Mereka mencoba berbicara dengannya setiap hari untuk memberitahunya bahwa mereka masih hidup di tengah pengepungan, pemboman hebat, dan kekurangan pasokan penting.
Pemadaman telekomunikasi dan kemacetan yang berulang di Gaza membuat banyak orang harus naik ke atap untuk mendapatkan sinyal, mencari penguat sinyal, atau menggunakan kartu eSIM yang terhubung ke operator telekomunikasi regional mana pun.
Ahed mengatakan dia melihat sebuah tank Israel berukuran luar biasa besar di luar gedung, tapi dia tidak terlalu memikirkannya karena rumah mereka telah dikelilingi oleh kendaraan tentara setelah gencatan senjata antara Israel dan Hamas berakhir pada bulan November.
Dia duduk dan bersiap untuk menghubungi nomor ayahnya.
"Saya berhasil mengatakan 'Saya hidup'. “Saya menyilangkan kaki dan tiba-tiba, saya terbalik,” katanya.
Ahed kehilangan salah satu anggota tubuhnya – hampir seluruh betis kanannya – dan mengeluarkan banyak darah.
Keterkejutannya sangat parah sehingga dia terdiam, begitu pula saudara perempuannya – dia kemudian menyadari “Mona takut memanggilku kalau-kalau aku tidak menjawab”.
“Akhirnya, ketika saya memahami apa yang baru saja terjadi, saya berhasil mengatakan: ‘Saya hidup’.”
Sepupu laki-laki Ahed bergegas menggendongnya ke bawah. Dia ingat melihat ke bawah dan berteriak, bertanya kepada sepupunya apakah kakinya masih di sana karena dia tidak dapat melihatnya.
“Yang dilakukan sepupu saya hanyalah menutup mata,” kenangnya.
Satu-satunya tempat mereka bisa mendudukkan Ahed adalah di meja makan, tempat ibunya tadi sedang menguleni adonan roti, pemandangan umum di rumah-rumah di Gaza ketika pengepungan total Israel membuat makanan dan bahan pokok menjadi langka.
Seseorang berlari mencari pamannya, Hani, seorang ahli ortopedi dan satu-satunya dokter di antara 30 kerabat yang tinggal di gedung keluarga.
Hani telah mengirim istri dan empat anaknya keluar dari daerah kantong pada awal serangan, sementara dia tetap tinggal.
Maka, dia mendapati dirinya memandangi kaki keponakannya yang terputus dan mengetahui bahwa dia harus menyelamatkannya, tanpa persediaan medis, anestesi, atau bahkan kain kasa bersih.
Di Gaza saat ini, petugas medis harus melakukan prosedur tanpa bantuan apa pun, bahkan tanpa alat untuk mengendalikan rasa sakit, sebagai akibat dari kekurangan tenaga medis akibat pengepungan tersebut.
Hani harus mengambil pilihan yang sulit namun jelas: mengamputasi sisa kaki bagian bawah dan segera menjahit arteri agar keponakannya tidak mati kehabisan darah.
“Saya tidak punya apa-apa. Saya ingat tas kerja saya ada di kamar, jadi saya minta keponakan saya untuk mengambilnya… Tidak ada apa-apa di sana kecuali kain kasa yang tidak steril,” kata Hani.
Baca Juga
Hani tidak tahu bagaimana cara membersihkan luka atau mengendalikan pendarahan, sebuah tugas yang tampaknya mustahil tanpa jahitan.
Sementara itu, fasilitas medis terbesar di Gaza, Rumah Sakit al-Shifa, berjarak “lima menit perjalanan dengan mobil” namun tidak dapat dijangkau dan tidak dapat digunakan karena pertempuran tersebut, kata Hani.
Seperti kebanyakan rumah sakit di wilayah kantong tersebut, al-Shifa telah diserang dan digerebek pada bulan November, memaksa ribuan warga Palestina yang terluka dan terlantar di sana untuk melarikan diri dan membuat rumah sakit tersebut tidak dapat berfungsi lagi.
Hani melihat sekeliling ruangan dengan putus asa, mencari apa pun untuk membuat proses mengerikan itu lebih mudah ditangani. Di wastafel dapur, dia melihat spons dan wadah berisi sabun cuci piring.
“Saya mulai membersihkan lukanya tetapi merasakan mata Ahed menusuk saya. Dia memohon agar saya tidak memotong sisa kakinya,” kata Hani.
Hatinya hancur dan air mata membasahi wajahnya, mengetahui apa yang harus ia lakukan selagi Ahed sadar sepenuhnya.
“Saya bertanya-tanya orang mana yang bisa menanggung sakitnya amputasi tanpa anestesi,” kata Hani.
Maka dia mengoperasi keponakannya dengan pisau dapur dan menggunakan jarum dan benang dari peralatan menjahit untuk menjahit arteri terbesar.
Ketika ditanya bagaimana dia mampu menahan rasa sakit, Ahed mengatakan perasaan tenang yang aneh mengambil alih.
“Saya hanya membaca ayat-ayat Al-Quran sepanjang waktu,” katanya.
Untuk memperbaiki lukanya, keluarga tersebut harus mencuci kain kasa tersebut dengan air panas dan menjemurnya hingga kering sehingga pamannya dapat memasangkannya kembali ke kakinya.
Mengetahui Ahed rentan terhadap infeksi, Hani mengatakan bahwa dia meminum “semua pil antibiotik dan obat penghilang rasa sakit yang ada di rumah,” dan membagikannya kepada Ahed, kebanyakan saat perut kosong karena tidak ada makanan.
Baru lima hari kemudian Hani dapat memindahkannya ke fasilitas medis – satu hari setelah tank Israel mundur dari daerah tersebut. Di sana, Ahed menjalani beberapa operasi, termasuk salah satunya untuk memperbaiki kaki kirinya yang patah.
Tapi itu masih belum cukup, kata Hani.
“Dia membutuhkan lebih banyak lagi… operasi perbaikan kosmetik untuk kakinya yang diamputasi, sebuah anggota tubuh palsu,” kata Hani.
“Saya bisa saja pergi bersama istri dan anak-anak saya, tapi Tuhan membiarkan saya tetap tinggal. Aku tinggal di sini agar Ahed bisa hidup.”
Ahed adalah salah satu generasi muda yang diamputasi yang muncul dari daerah kantong tersebut akibat serangan Israel yang tiada henti.
Menurut Dana Anak-Anak PBB, lebih dari 10 anak kehilangan satu atau kedua kaki mereka setiap hari di Gaza sejak 7 Oktober. Itu berarti lebih dari 1.000 anak.
Praktik Standar
Para profesional medis mengatakan banyak dari mereka yang tewas di Gaza sejak 7 Oktober sebenarnya bisa diselamatkan jika mereka bisa mencapai rumah sakit.
Abed, seorang dokter ortopedi dari Doctors Without Borders – juga dikenal sebagai Medecins Sans Frontieres (MSF) – mengatakan petugas medis di Gaza bergantung pada obat penenang pasien di tengah kurangnya anestesi.
“Kami kekurangan semua jenis obat,” kata Abed, yang selama ini bekerja di Rumah Sakit Lapangan Indonesia Rafah dan meminta agar hanya nama depannya yang disebutkan karena alasan keamanan.
“Kami bergantung pada obat pereda nyeri seperti parasetamol dan kami mencoba anestesi lokal untuk mengurangi rasa sakit,” katanya.
Menurut Abed, pasien menjalani “ amputasi traumatis ” setiap hari, dan sebagian besar pasien adalah anak-anak.
Ketika sebuah rumah sakit menampung banyak orang yang terluka, diperlukan waktu berjam-jam bagi seseorang untuk sampai ke ruang operasi, sehingga penyelamatan anggota tubuh menjadi tidak mungkin dan amputasi diperlukan “untuk menyelamatkan nyawa pasien”, katanya.
Menurut Kementerian Kesehatan di Gaza, Israel telah menewaskan hampir 27.000 orang dan melukai sekitar 65.000 lainnya dalam serangannya di Gaza sejak 7 Oktober. Hampir seperempat korban cedera terjadi pada anak-anak, kata kementerian tersebut.
Ahed mengatakan dia selamanya berubah. Sebelum penyerangan, dia terdaftar untuk belajar farmasi. Tapi sekarang dia tidak tahan “apapun yang berhubungan dengan obat-obatan” karena apa yang telah dia alami.
“Saya akan mengubah jurusan saya,” katanya. “Saya akan menjadi seorang desainer interior dan membuktikan kepada dunia bahwa saya masih bisa menjalani kehidupan normal meskipun saya memiliki cacat fisik.”
(mhy)
Lihat Juga :