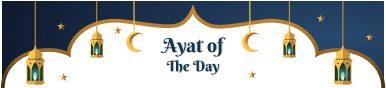NU Pernah Melarang Ibadah Haji, Begini Alasannya
Rabu, 17 Juni 2020 - 18:51 WIB
Kebersihan harta sebagai penggerak manasik haji itu sendiri mesti dipastikan. Bukan asal berangkat haji. Foto/Ilustrasi/SINDOnews
Pada masa revolusi, Nahdlatul Ulama atau NU sempat melarang pelaksanaan ibadah haji . Ceritanya, kapal sebagai sarana transportasi haji belum dimiliki oleh bangsa Indonesia. Karena itu bila pergi haji naik kapal milik orang Belanda yang kala itu menjajah bangsa Indonesia.
Kisah pelarangan haji ini dicatat oleh sejarawan NU, Abdul Mun’im DZ dalam Fragmen Sejarah NU (2017). Kala itu, gejolak revolusi menyebabkan umat Islam risau karena perjalanan haji terhenti. Haji tidak bisa diselenggarakan karena faktor keamanan.
Melihat situasi itu, Gubernur Hindia-Belanda, Van der Plaas mengambil tindakan untuk menolong umat Islam. Belanda mengumumkan bagi yang hendak melaksanakan ibadah haji disediakan fasilitas selengkapnya dan dijamin keamanannya.
Tawaran Kolonial Belanda itu menggoda umat Islam yang kebetulan selama beberapa tahun dalam gelora revolusi itu perjalanan ibadah haji terganggu, saat ini Belanda menjamin fasilitas untuk mereka, maka banyak yang mendaftar untuk menunaikan ibadah haji.
Sekilas kebijakan tersebut nampak populis, padahal itu mengandung intrik politik untuk meraup simpati umat Islam Indonesia.
Nah, di tengah kegairahan umat Islam untuk berhaji, Rais Akbar NU, Hadhratussyekh KH Hasyim Asy’ari justru mengeluarkan fatwa bahwa melakukan ibadah haji saat ini hukumnya tidak sah. Ibadah haji memang sebuah kewajiban bila syarat rukunnya terlengkapi.
Sementara pada saat itu Indonesia dalam keadaan perang, kapal sebagai sarana transportasi haji belum dimiliki oleh bangsa Indonesia. Karena itu bila pergi haji naik kapal milik orang Belanda (yang dianggap kafir), maka hajinya tidak sah.
Fatwa itu membuat umat Islam tertegun, tetapi bagaimana pun dengan hujjah-nya yang kuat dan sesuai nalar, maka seberat apapun fatwa itu mesti ditaati, umat Islam banyak yang membatalkan perjalanan hajinya. Tentu saja hal itu membuat Belanda geram. Usahanya gagal dalam mempengaruhi hati umat Islam agar tidak memihak pada republik pimpinan Soekarno-Hatta.
Jauh sebelum era revolusi, yaitu pada 1824-1859, Hindia Belanda justru melakukan pengetatan pemberangkatan haji. Kolonial menilai bahwa haji menjadi ancaman eksistensi kolonial di Indonesia. Makna politis ibadah haji baru dirasakan secara serius tatkala negara Hindia Belanda berdiri sebagai penerus kekuasaan VOC. Mereka menganggap, seseorang yang pulang dari ibadah haji mempunyai potensi menggerakkan rakyat untuk melakukan pemberontakan terhadap kolonial.
ahi Munkar
Segala upaya dilakukan oleh Hindia Belanda, dari mulai pengetatan pemberangkatan dan aturan-aturan lain setelah pulang dari tanah suci. Kekhawatiran pemerintah kolonial tercermin dalam Ordonansi Haji tahun 1825, berisi pembatasan dan pengetatan jumlah haji yang berangkat. Salah satu cara untuk merealisasikannya adalah menaikkan biaya haji.
Beberapa dekade kemudian, pada tahun 1859, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan ordonansi baru menyangkut urusan haji. Meski lebih longgar dari aturan sebelumnya, di sana-sini masih ada berbagai pengetatan.
.
Yang paling menonjol dari ordonansi baru ini adalah pemberlakuan semacam “ujian haji” bagi mereka yang baru pulang dari Tanah suci. Mereka harus membuktikan benar-benar telah mengunjungi Mekkah. Jika seseorang sudah dianggap lulus ujian ini, ia berhak menyandang gelar haji dan diwajibkan mengenakan pakaian khusus haji (jubah, serban putih, atau kopiah putih).
Dari sini bisa disimak bahwa fatwa KH Hasyim Asy’ari yang melarang haji tak sekadar berdalil karena menggunakan kapal milik orang Belanda. Lebih jauh lagi, ini adalah perlawanan para kiyai terhadap politisasi haji.
Hukum Haji
Meski bersifat fardu ain, dalam ilmu fiqih yang terangkum pada Ensiklopedia Fikih Indonesia 6: Haji dan Umrah, Bab 3 tentang Hukum-hukum Haji, Ahmad Sarwat, menyebut hukum haji bisa tidak sah jika biaya pelaksanaan ibadah ini didapat dari jalan yang tidak benar, misal hasil merampok, menipu, mencuri, membungakan uang, korupsi, suap dan lainnya.
Lebih jauh lagi, mazhab Hanbali menganggap ibadah haji yang dibiayai dengan harta yang haram juga tidak sah. Karenanya jamaah yang menunaikan ibadah haji dengan harta yang haram masih tetap berkewajiban untuk menunaikan ibadah haji di tahun-tahun selanjutnya mengingat hajinya dengan harta haram itu tidak sah.
يستحب أن يحرص على مال حلال لينفقه في سفره فإن الله طيب لا يقبل إِلا طيباً ؛ وفي الخبر : ( مَنْ حَجَّ بمال حَرَامٍ إذا لَبَّى قيل له لا لَبَّيْكَ ولا سَعْدَيْكَ وحَجُّكَ مَرْدُودٌ عَلَيْكَ ) . ومن حج بمال مغصوب أجزأه الحج وإن كان عاصياً بالغصب ، وقال أحمد : لا يجزئه اه م د على التحرير
Artinya, “Seseorang dianjurkan untuk betul-betul mencari harta halal, agar ia dapat menggunakannya di masa perjalanannya. Karena sungguh Allah itu suci, tidak menerima kecuali yang suci. Di dalam hadis dikatakan, ‘Siapa berhaji dengan harta haram, kalau ia berkata ‘labbaik’, maka dijawab malaikat, ‘La labbaik, wala sa’daik, hajimu tertolak’.’ Karenanya siapa yang berhaji dengan harta haram, maka hajinya memadai sekalipun ia bermaksiat karena merampas. Sementara Imam Ahmad berkata, hajinya tidak cukup,” (Lihat Sulaiman Al-Bujairimi, Hasyiyatul Bujairimi alal Khatib, Beirut, Darul Kutub Al-Ilmiyah, 1996 M/1417 H, juz 3, halaman 181).
Hanya saja, mazhab Hanafi , Maliki , dan Syafi’i tidak sependapat. Mazhab ini berpandangan haji yang dibiayai dengan harta yang haram tetap sah meskipun ia berdosa atas kesalahannya memperoleh harta haram itu sebagaimana kutipan berikut ini.
وَيَسْقُطُ فَرْضُ مَنْ حَجَّ بِمَالٍ حَرَامٍ ) كَمَغْصُوبٍ وَإِنْ كَانَ عَاصِيًا كَمَا فِي الصَّلَاةِ فِي مَغْصُوبٍ أَوْ ثَوْبِ حَرِير
Artinya, “(Gugurlah kewajiban orang yang berhaji dengan harta haram) seperti harta rampasan sekalipun ia bermaksiat. Sama halnya dengan shalat di tempat hasil rampasan atau mengenakan pakaian terbuat dari sutra,” (Lihat Abu Zakariya Al-Anshari, Asnal Mathalib, juz 6, halaman 51).
Syekh Abu Zakariya Al-Anshari secara tegas mengatakan bahwa jamaah yang membiayai hajinya dengan harta haram itu sama seperti orang yang bersembahyang dengan mengenakan pakaian hasil merampas atau sutra, pakaian yang diharamkan bagi pria. Artinya ibadah haji dan salat orang yang bersangkutan tetap sah. Dengan demikian gugurlah tuntutan wajib ibadah dari orang tersebut.
Kalangan Hanafi, Maliki, dan Syafi’i mengeluarkan argumentasi bahwa haji itu sendiri adalah kunjungan ke tempat-tempat istimewa dalam agama. Dan itu tidak dilarang. Yang dilarang agama itu adalah menggunakan harta yang haram itu seperti untuk keperluan haji.
Jadi keduanya tidak berkaitan sama sekali. Sama halnya dengan orang sembahyang di tanah rampasan (hasil kezaliman). Sembahyangnya sendiri itu tetap sah. Tetapi menempati tanah yang diharamkan itu yang dilarang oleh agama. Karenanya ibadah haji atau salat tidak bisa disifatkan haram. Meskipun gugur kewajiban ibadah itu, namun manasik haji tidak diterima dan tidak mendapatkan pahala dari Allah. Nasib manasik hajinya sama seperti orang sembahyang tetapi riya, atau berpuasa tetapi mengghibah. Semuanya tidak diganjar pahala. Demikian argumentasi yang diajukan Ibnu Abidin dalam Haysiyah Raddul Mukhtar, Beirut, Darul Fikr, 2000 M/1421 H, Juz 2 halaman 456).
Sementara mazhab Hanbali sepakat dengan jumhur ulama perihal penerimaan dan pahala. Mereka yang menunaikan ibadah haji dengan harta haram tidak menerima pahala. Sedangkan terkait keabsahan, mazhab Hanbali menyatakan bahwa haji yang dibiayai dengan harta haram tidak sah. Karenanya mereka harus mengulang hajinya pada tahun depan karena hajinya tahun ini tidak sah. Karena tidak bisa mencampurkan antara ibadah dengan hal-hal batil.
Pendapat mazhab Hanbali tersebut perlu dipelajari lebih lanjut dari sisi moralitas ibadah. Semangat Mazhab Hanbali bisa jadi mengantisipasi kemungkinan orang melakukan pencucian uang dengan menunaikan ibadah haji. Dengan demikian haji bukan hanya dipandang secara rangkaian upacara formal. Tetapi kebersihan harta sebagai penggerak manasik haji itu sendiri mesti dipastikan. Bukan asal berangkat haji.
Pandangan mazhab Hanbali bisa secara moral menghentikan kezaliman, suap, kecurangan, korupsi atau kejahatan umat Islam dalam menjalankan praktik bisnis, mengemban jabatan publik, atau menjalani kesehariannya sebagai pegawai negeri sipil, dan profesi lainnya. ( )
Kisah pelarangan haji ini dicatat oleh sejarawan NU, Abdul Mun’im DZ dalam Fragmen Sejarah NU (2017). Kala itu, gejolak revolusi menyebabkan umat Islam risau karena perjalanan haji terhenti. Haji tidak bisa diselenggarakan karena faktor keamanan.
Melihat situasi itu, Gubernur Hindia-Belanda, Van der Plaas mengambil tindakan untuk menolong umat Islam. Belanda mengumumkan bagi yang hendak melaksanakan ibadah haji disediakan fasilitas selengkapnya dan dijamin keamanannya.
Tawaran Kolonial Belanda itu menggoda umat Islam yang kebetulan selama beberapa tahun dalam gelora revolusi itu perjalanan ibadah haji terganggu, saat ini Belanda menjamin fasilitas untuk mereka, maka banyak yang mendaftar untuk menunaikan ibadah haji.
Sekilas kebijakan tersebut nampak populis, padahal itu mengandung intrik politik untuk meraup simpati umat Islam Indonesia.
Baca Juga
Nah, di tengah kegairahan umat Islam untuk berhaji, Rais Akbar NU, Hadhratussyekh KH Hasyim Asy’ari justru mengeluarkan fatwa bahwa melakukan ibadah haji saat ini hukumnya tidak sah. Ibadah haji memang sebuah kewajiban bila syarat rukunnya terlengkapi.
Sementara pada saat itu Indonesia dalam keadaan perang, kapal sebagai sarana transportasi haji belum dimiliki oleh bangsa Indonesia. Karena itu bila pergi haji naik kapal milik orang Belanda (yang dianggap kafir), maka hajinya tidak sah.
Fatwa itu membuat umat Islam tertegun, tetapi bagaimana pun dengan hujjah-nya yang kuat dan sesuai nalar, maka seberat apapun fatwa itu mesti ditaati, umat Islam banyak yang membatalkan perjalanan hajinya. Tentu saja hal itu membuat Belanda geram. Usahanya gagal dalam mempengaruhi hati umat Islam agar tidak memihak pada republik pimpinan Soekarno-Hatta.
Jauh sebelum era revolusi, yaitu pada 1824-1859, Hindia Belanda justru melakukan pengetatan pemberangkatan haji. Kolonial menilai bahwa haji menjadi ancaman eksistensi kolonial di Indonesia. Makna politis ibadah haji baru dirasakan secara serius tatkala negara Hindia Belanda berdiri sebagai penerus kekuasaan VOC. Mereka menganggap, seseorang yang pulang dari ibadah haji mempunyai potensi menggerakkan rakyat untuk melakukan pemberontakan terhadap kolonial.
ahi Munkar
Segala upaya dilakukan oleh Hindia Belanda, dari mulai pengetatan pemberangkatan dan aturan-aturan lain setelah pulang dari tanah suci. Kekhawatiran pemerintah kolonial tercermin dalam Ordonansi Haji tahun 1825, berisi pembatasan dan pengetatan jumlah haji yang berangkat. Salah satu cara untuk merealisasikannya adalah menaikkan biaya haji.
Beberapa dekade kemudian, pada tahun 1859, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan ordonansi baru menyangkut urusan haji. Meski lebih longgar dari aturan sebelumnya, di sana-sini masih ada berbagai pengetatan.
.
Yang paling menonjol dari ordonansi baru ini adalah pemberlakuan semacam “ujian haji” bagi mereka yang baru pulang dari Tanah suci. Mereka harus membuktikan benar-benar telah mengunjungi Mekkah. Jika seseorang sudah dianggap lulus ujian ini, ia berhak menyandang gelar haji dan diwajibkan mengenakan pakaian khusus haji (jubah, serban putih, atau kopiah putih).
Dari sini bisa disimak bahwa fatwa KH Hasyim Asy’ari yang melarang haji tak sekadar berdalil karena menggunakan kapal milik orang Belanda. Lebih jauh lagi, ini adalah perlawanan para kiyai terhadap politisasi haji.
Hukum Haji
Meski bersifat fardu ain, dalam ilmu fiqih yang terangkum pada Ensiklopedia Fikih Indonesia 6: Haji dan Umrah, Bab 3 tentang Hukum-hukum Haji, Ahmad Sarwat, menyebut hukum haji bisa tidak sah jika biaya pelaksanaan ibadah ini didapat dari jalan yang tidak benar, misal hasil merampok, menipu, mencuri, membungakan uang, korupsi, suap dan lainnya.
Lebih jauh lagi, mazhab Hanbali menganggap ibadah haji yang dibiayai dengan harta yang haram juga tidak sah. Karenanya jamaah yang menunaikan ibadah haji dengan harta yang haram masih tetap berkewajiban untuk menunaikan ibadah haji di tahun-tahun selanjutnya mengingat hajinya dengan harta haram itu tidak sah.
يستحب أن يحرص على مال حلال لينفقه في سفره فإن الله طيب لا يقبل إِلا طيباً ؛ وفي الخبر : ( مَنْ حَجَّ بمال حَرَامٍ إذا لَبَّى قيل له لا لَبَّيْكَ ولا سَعْدَيْكَ وحَجُّكَ مَرْدُودٌ عَلَيْكَ ) . ومن حج بمال مغصوب أجزأه الحج وإن كان عاصياً بالغصب ، وقال أحمد : لا يجزئه اه م د على التحرير
Artinya, “Seseorang dianjurkan untuk betul-betul mencari harta halal, agar ia dapat menggunakannya di masa perjalanannya. Karena sungguh Allah itu suci, tidak menerima kecuali yang suci. Di dalam hadis dikatakan, ‘Siapa berhaji dengan harta haram, kalau ia berkata ‘labbaik’, maka dijawab malaikat, ‘La labbaik, wala sa’daik, hajimu tertolak’.’ Karenanya siapa yang berhaji dengan harta haram, maka hajinya memadai sekalipun ia bermaksiat karena merampas. Sementara Imam Ahmad berkata, hajinya tidak cukup,” (Lihat Sulaiman Al-Bujairimi, Hasyiyatul Bujairimi alal Khatib, Beirut, Darul Kutub Al-Ilmiyah, 1996 M/1417 H, juz 3, halaman 181).
Hanya saja, mazhab Hanafi , Maliki , dan Syafi’i tidak sependapat. Mazhab ini berpandangan haji yang dibiayai dengan harta yang haram tetap sah meskipun ia berdosa atas kesalahannya memperoleh harta haram itu sebagaimana kutipan berikut ini.
وَيَسْقُطُ فَرْضُ مَنْ حَجَّ بِمَالٍ حَرَامٍ ) كَمَغْصُوبٍ وَإِنْ كَانَ عَاصِيًا كَمَا فِي الصَّلَاةِ فِي مَغْصُوبٍ أَوْ ثَوْبِ حَرِير
Artinya, “(Gugurlah kewajiban orang yang berhaji dengan harta haram) seperti harta rampasan sekalipun ia bermaksiat. Sama halnya dengan shalat di tempat hasil rampasan atau mengenakan pakaian terbuat dari sutra,” (Lihat Abu Zakariya Al-Anshari, Asnal Mathalib, juz 6, halaman 51).
Syekh Abu Zakariya Al-Anshari secara tegas mengatakan bahwa jamaah yang membiayai hajinya dengan harta haram itu sama seperti orang yang bersembahyang dengan mengenakan pakaian hasil merampas atau sutra, pakaian yang diharamkan bagi pria. Artinya ibadah haji dan salat orang yang bersangkutan tetap sah. Dengan demikian gugurlah tuntutan wajib ibadah dari orang tersebut.
Kalangan Hanafi, Maliki, dan Syafi’i mengeluarkan argumentasi bahwa haji itu sendiri adalah kunjungan ke tempat-tempat istimewa dalam agama. Dan itu tidak dilarang. Yang dilarang agama itu adalah menggunakan harta yang haram itu seperti untuk keperluan haji.
Jadi keduanya tidak berkaitan sama sekali. Sama halnya dengan orang sembahyang di tanah rampasan (hasil kezaliman). Sembahyangnya sendiri itu tetap sah. Tetapi menempati tanah yang diharamkan itu yang dilarang oleh agama. Karenanya ibadah haji atau salat tidak bisa disifatkan haram. Meskipun gugur kewajiban ibadah itu, namun manasik haji tidak diterima dan tidak mendapatkan pahala dari Allah. Nasib manasik hajinya sama seperti orang sembahyang tetapi riya, atau berpuasa tetapi mengghibah. Semuanya tidak diganjar pahala. Demikian argumentasi yang diajukan Ibnu Abidin dalam Haysiyah Raddul Mukhtar, Beirut, Darul Fikr, 2000 M/1421 H, Juz 2 halaman 456).
Sementara mazhab Hanbali sepakat dengan jumhur ulama perihal penerimaan dan pahala. Mereka yang menunaikan ibadah haji dengan harta haram tidak menerima pahala. Sedangkan terkait keabsahan, mazhab Hanbali menyatakan bahwa haji yang dibiayai dengan harta haram tidak sah. Karenanya mereka harus mengulang hajinya pada tahun depan karena hajinya tahun ini tidak sah. Karena tidak bisa mencampurkan antara ibadah dengan hal-hal batil.
Pendapat mazhab Hanbali tersebut perlu dipelajari lebih lanjut dari sisi moralitas ibadah. Semangat Mazhab Hanbali bisa jadi mengantisipasi kemungkinan orang melakukan pencucian uang dengan menunaikan ibadah haji. Dengan demikian haji bukan hanya dipandang secara rangkaian upacara formal. Tetapi kebersihan harta sebagai penggerak manasik haji itu sendiri mesti dipastikan. Bukan asal berangkat haji.
Pandangan mazhab Hanbali bisa secara moral menghentikan kezaliman, suap, kecurangan, korupsi atau kejahatan umat Islam dalam menjalankan praktik bisnis, mengemban jabatan publik, atau menjalani kesehariannya sebagai pegawai negeri sipil, dan profesi lainnya. ( )
(mhy)
Lihat Juga :