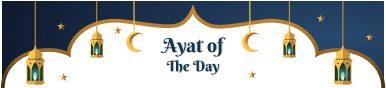4 Penyebab Perbedaan Pendapat Ulama dalam Menentukan Hukum Nikah Misyar
Rabu, 01 November 2023 - 05:15 WIB
Sebagian ulama memilih tawaqquf (abstain) tentang hukum nikah Misyar. Ilustrasi: Ist
Chomim Tohari mengatakan sebagian ulama memilih tawaqquf (abstain) tentang hukum nikah misyar , lantaran menurut mereka esensi pernikahan seperti ini berikut dalil yang dipergunakan baik yang mendukung maupun yang menolak tampak belum jelas dan meyakinkan.
"Mereka menyatakan bahwa sangat penting untuk dilakukan pengkajian mendalam dan pencermatan ekstra perihal nikah misyar ini," tulis Chomim Tohari dalam papernya berjudul "Fatwa Ulama tentang Hukum Islam Nikah Misyar Perspektif Maqqasid Shari'ah"
Di antara ulama kontemporer yang mengambil posisi ini adalah Shaykh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin.
Chomim Tohari mengatakan pembahasan di atas menunjukkan bahwa para ulama hingga kini belum mencapai kesepakatan tentang hukum nikah misyar. Karena nikah misyar merupakan masalah baru dan belum ditemukan dasar hukum yang kuat untuk menghukuminya, maka sewajarnya manakala terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama.
Menurut Chomim Tohari, beberapa hal yang menjadi sebab perbedaan pendapat tersebut adalah:
Pertama, perbedaan manhaj dalam menetapkan hukum. Antara kelompok yang membolehkan dan yang melarang pernikahan misyar sama-sama menggunakan dalil akal dalam menentukan hukumnya.
Namun letak perbedaannya adalah kelompok yang membolehkan nikah misyar (seperti Yusuf alQardhawi ) lebih banyak menggunakan pendekatan kemaslahatan (istislahi) yang dapat dicapai dalam pernikahan ini. Meskipun alQardhawi juga menggunakan qiyas -yakni mengqiyaskan nikah misyar dengan kasus Saudah istri Nabi yang memberikan hak malamnya untuk Aisyah - namun dengan proporsi yang kecil.
Sementara kelompok yang menentang nikah misyar tampaknya lebih mengedepankan qiyas antara nikah misyar dengan nikah biasa. Sehingga adanya perbedaan-perbedaan antara nikah misyar dengan nikah biasa, menyebabkan nikah misyar dianggap sebagai pernikahan yang tidak sah, sehingga harus diharamkan.
Selain itu, kelompok yang melarang nikah misyar lebih banyak melihat aspek mudharat yang dihasilkan dari jenis pernikahan ini.
Menurut Chomim Tohari, dari perspektif ilmu ushul fiqh, kelompok yang menolak nikah misyar mengharamkan pernikahan jenis ini dengan metode sadd ad-dharih. Artinya, menutup jalan yang menuju kepada kerusakan.
Kedua, perbedaan dalam penetapan kriteria keabsahan nikah. Chomim Tohari mengatakan sebagaimana diketahui bahwa di antara alasan yang dikemukakan oleh para ulama yang membolehkan nikah misyar adalah selama suatu pernikahan terpenuhi syarat dan rukunnya, maka pernikahan itu sah.
Sedangkan ulama yang mengharamkan nikah misyar berpandangan bahwa keabsahan pernikahan tidak semata-mata tercapainya syarat dan rukun pernikahan, tetapi juga harus terwujud tujuan-tujuan pernikahan.
Jadi, kriteria pernikahan yang sah menurut ulama yang membolehkan nikah misyar adalah pernikahan yang terpenuhi syarat dan rukunnya. Sedangkan kriteria pernikahan yang sah menurut ulama yang mengharamkan nikah misyar adalah pernikahan yang tidak hanya terpenuhi syarat dan rukunnya, tetapi sekaligus tujuan-tujuan pernikahan tersebut.
Ketiga, perbedaan dalam memahami wajib tidaknya sosialisasi suatu pernikahan. Pernikahan misyar (meskipun tidak semuanya) biasanya mengandung unsur kerahasiaan antara pihak yang melakukan nikah misyar dengan istri pertama dan keluarganya.
Perdebatan tentang akibat hukum merahasiakan pernikahan ini sebenarnya telah terjadi pada masa lalu antara para ulama mazhab. Mazhab Maliki misalnya, berpendapat bahwa misi pernikahan adalah pemberitahuan dan sosialisasi. Syarat adanya sosialisasi merupakan syarat sahnya suatu pernikahan.
Dengan adanya permintaan untuk dirahasiakan, baik oleh kedua suami istri, wali, maupun saksi, berarti tidak terwujud misi pemberitahuan dan sosialisasi.
Selain itu, merahasiakan hubungan pernikahan dianggap termasuk ciri-ciri perzinaan. Sehingga pernikahan manakala sudah diminta untuk disembunyikan, maka mirip dengan praktik perzinaan, maka akibatnya rusak secara hukum.
Demikian pandangan mazhab Maliki, yang kemudian diikuti oleh kelompok ulama yang mengharamkan nikah misyar.
Adapun kelompok yang membolehkan nikah misyar berpedoman pada pendapat jumhur ulama mazhab Hanafi, Syafi’i, serta Hanbali yang menyatakan bahwa pernikahan yang telah terpenuhi syarat dan rukunnya, meskipun suami, istri, wali maupun kedua saksi bersepakat untuk merahasiakan pernikahan tersebut dari pengetahuan masyarakat, maka pernikahan itu adalah tetap sah hukumnya.
Menurut jumhur ulama, adanya dua orang saksi telah cukup untuk mengatakan bahwa pernikahan tersebut tidak lagi bersifat rahasia. Namun menyembunyikan pernikahan dapat dihukumi makruh agar tidak muncul tuduhan miring kepada kedua pihak yang melaksanakan pernikahan itu.
Keempat, perbedaan dalam menentukan syarat-syarat yang membatalkan pernikahan. Menurut pihak yang mengharamkan nikah misyar, adanya syarat bahwa suami tidak menafkahi istri, tidak memberi tempat tinggal, serta tidak membagi malamnya dengan istri yang dinikahi secara misyar, serta beberapa kewajiban sejenis yang ditetapkan syari’at atas suami termasuk syaratsyarat ilegal (bathil).
Sehingga pada kelompok ulama yang menolak nikah misyar ada yang menganggap nikah misyar karena syaratnya bathil, maka pernikahannya juga tidak sah.
Sedangkan yang lain menyatakan pernikahannya tetap sah, tetapi syaratnya bathil, maka dari itu tetap mengimplikasikan pengaruh-pengaruh syari’at berupa penghalalan senggama, kepastian nasab, kewajiban nafkah dan pembagian yang adil (jika poligami).
Dalam hal ini, istri berhak menuntut, namun tidak masalah jika ia dengan sukarela melepaskan hak-hak ini tanpa syarat, sebab itu merupakan haknya.
Pendapat seperti ini dianut oleh Shaykh Abu Malik Kamal bin al-Sayyid Salim yang menurut Chomim Tohari adalah bentuk pengingkaran terhadap keabsahan nikah misyar.
Sedangkan ulama yang membolehkan nikah misyar, mengenai masalah ini berpendapat bahwa adanya syarat-syarat seperti suami tidak menafkahi istri, tidak memberi tempat tinggal, serta tidak membagi malamnya dengan istri yang dinikahi secara misyar, bukanlah syarat yang menyebabkan pernikahan tersebut batil (tidak sah).
Adanya syarat-syarat tersebut dapat diterima dengan syarat pula bahwa sang istri merelakan tidak terpenuhinya sebagian hak-haknya dalam pernikahan dengan tanpa paksaan dari pihak manapun. Akan tetapi, seandainya pada suatu saat istri bermaksud menuntut haknya kembali, maka ia berhak menuntutnya, dan pernikahan tetaplah sah tanpa ada sesuatupun yang membatalkannya.
"Poin-poin di atas menjadi sebab perbedaan pendapat para ulama dalam menentukan hukum nikah misyar," demikian Chomim Tohari.
"Mereka menyatakan bahwa sangat penting untuk dilakukan pengkajian mendalam dan pencermatan ekstra perihal nikah misyar ini," tulis Chomim Tohari dalam papernya berjudul "Fatwa Ulama tentang Hukum Islam Nikah Misyar Perspektif Maqqasid Shari'ah"
Di antara ulama kontemporer yang mengambil posisi ini adalah Shaykh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin.
Chomim Tohari mengatakan pembahasan di atas menunjukkan bahwa para ulama hingga kini belum mencapai kesepakatan tentang hukum nikah misyar. Karena nikah misyar merupakan masalah baru dan belum ditemukan dasar hukum yang kuat untuk menghukuminya, maka sewajarnya manakala terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama.
Menurut Chomim Tohari, beberapa hal yang menjadi sebab perbedaan pendapat tersebut adalah:
Pertama, perbedaan manhaj dalam menetapkan hukum. Antara kelompok yang membolehkan dan yang melarang pernikahan misyar sama-sama menggunakan dalil akal dalam menentukan hukumnya.
Namun letak perbedaannya adalah kelompok yang membolehkan nikah misyar (seperti Yusuf alQardhawi ) lebih banyak menggunakan pendekatan kemaslahatan (istislahi) yang dapat dicapai dalam pernikahan ini. Meskipun alQardhawi juga menggunakan qiyas -yakni mengqiyaskan nikah misyar dengan kasus Saudah istri Nabi yang memberikan hak malamnya untuk Aisyah - namun dengan proporsi yang kecil.
Sementara kelompok yang menentang nikah misyar tampaknya lebih mengedepankan qiyas antara nikah misyar dengan nikah biasa. Sehingga adanya perbedaan-perbedaan antara nikah misyar dengan nikah biasa, menyebabkan nikah misyar dianggap sebagai pernikahan yang tidak sah, sehingga harus diharamkan.
Selain itu, kelompok yang melarang nikah misyar lebih banyak melihat aspek mudharat yang dihasilkan dari jenis pernikahan ini.
Menurut Chomim Tohari, dari perspektif ilmu ushul fiqh, kelompok yang menolak nikah misyar mengharamkan pernikahan jenis ini dengan metode sadd ad-dharih. Artinya, menutup jalan yang menuju kepada kerusakan.
Kedua, perbedaan dalam penetapan kriteria keabsahan nikah. Chomim Tohari mengatakan sebagaimana diketahui bahwa di antara alasan yang dikemukakan oleh para ulama yang membolehkan nikah misyar adalah selama suatu pernikahan terpenuhi syarat dan rukunnya, maka pernikahan itu sah.
Sedangkan ulama yang mengharamkan nikah misyar berpandangan bahwa keabsahan pernikahan tidak semata-mata tercapainya syarat dan rukun pernikahan, tetapi juga harus terwujud tujuan-tujuan pernikahan.
Jadi, kriteria pernikahan yang sah menurut ulama yang membolehkan nikah misyar adalah pernikahan yang terpenuhi syarat dan rukunnya. Sedangkan kriteria pernikahan yang sah menurut ulama yang mengharamkan nikah misyar adalah pernikahan yang tidak hanya terpenuhi syarat dan rukunnya, tetapi sekaligus tujuan-tujuan pernikahan tersebut.
Ketiga, perbedaan dalam memahami wajib tidaknya sosialisasi suatu pernikahan. Pernikahan misyar (meskipun tidak semuanya) biasanya mengandung unsur kerahasiaan antara pihak yang melakukan nikah misyar dengan istri pertama dan keluarganya.
Perdebatan tentang akibat hukum merahasiakan pernikahan ini sebenarnya telah terjadi pada masa lalu antara para ulama mazhab. Mazhab Maliki misalnya, berpendapat bahwa misi pernikahan adalah pemberitahuan dan sosialisasi. Syarat adanya sosialisasi merupakan syarat sahnya suatu pernikahan.
Dengan adanya permintaan untuk dirahasiakan, baik oleh kedua suami istri, wali, maupun saksi, berarti tidak terwujud misi pemberitahuan dan sosialisasi.
Selain itu, merahasiakan hubungan pernikahan dianggap termasuk ciri-ciri perzinaan. Sehingga pernikahan manakala sudah diminta untuk disembunyikan, maka mirip dengan praktik perzinaan, maka akibatnya rusak secara hukum.
Demikian pandangan mazhab Maliki, yang kemudian diikuti oleh kelompok ulama yang mengharamkan nikah misyar.
Adapun kelompok yang membolehkan nikah misyar berpedoman pada pendapat jumhur ulama mazhab Hanafi, Syafi’i, serta Hanbali yang menyatakan bahwa pernikahan yang telah terpenuhi syarat dan rukunnya, meskipun suami, istri, wali maupun kedua saksi bersepakat untuk merahasiakan pernikahan tersebut dari pengetahuan masyarakat, maka pernikahan itu adalah tetap sah hukumnya.
Menurut jumhur ulama, adanya dua orang saksi telah cukup untuk mengatakan bahwa pernikahan tersebut tidak lagi bersifat rahasia. Namun menyembunyikan pernikahan dapat dihukumi makruh agar tidak muncul tuduhan miring kepada kedua pihak yang melaksanakan pernikahan itu.
Keempat, perbedaan dalam menentukan syarat-syarat yang membatalkan pernikahan. Menurut pihak yang mengharamkan nikah misyar, adanya syarat bahwa suami tidak menafkahi istri, tidak memberi tempat tinggal, serta tidak membagi malamnya dengan istri yang dinikahi secara misyar, serta beberapa kewajiban sejenis yang ditetapkan syari’at atas suami termasuk syaratsyarat ilegal (bathil).
Sehingga pada kelompok ulama yang menolak nikah misyar ada yang menganggap nikah misyar karena syaratnya bathil, maka pernikahannya juga tidak sah.
Sedangkan yang lain menyatakan pernikahannya tetap sah, tetapi syaratnya bathil, maka dari itu tetap mengimplikasikan pengaruh-pengaruh syari’at berupa penghalalan senggama, kepastian nasab, kewajiban nafkah dan pembagian yang adil (jika poligami).
Dalam hal ini, istri berhak menuntut, namun tidak masalah jika ia dengan sukarela melepaskan hak-hak ini tanpa syarat, sebab itu merupakan haknya.
Pendapat seperti ini dianut oleh Shaykh Abu Malik Kamal bin al-Sayyid Salim yang menurut Chomim Tohari adalah bentuk pengingkaran terhadap keabsahan nikah misyar.
Sedangkan ulama yang membolehkan nikah misyar, mengenai masalah ini berpendapat bahwa adanya syarat-syarat seperti suami tidak menafkahi istri, tidak memberi tempat tinggal, serta tidak membagi malamnya dengan istri yang dinikahi secara misyar, bukanlah syarat yang menyebabkan pernikahan tersebut batil (tidak sah).
Adanya syarat-syarat tersebut dapat diterima dengan syarat pula bahwa sang istri merelakan tidak terpenuhinya sebagian hak-haknya dalam pernikahan dengan tanpa paksaan dari pihak manapun. Akan tetapi, seandainya pada suatu saat istri bermaksud menuntut haknya kembali, maka ia berhak menuntutnya, dan pernikahan tetaplah sah tanpa ada sesuatupun yang membatalkannya.
"Poin-poin di atas menjadi sebab perbedaan pendapat para ulama dalam menentukan hukum nikah misyar," demikian Chomim Tohari.
(mhy)
Lihat Juga :