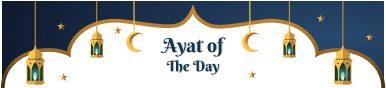Genosida Israel: Profesor Ini Bilang Warga Palestina Jadi Korban Supremasi Yahudi
Rabu, 20 Desember 2023 - 08:50 WIB
Klaim Israel, memberikan mereka hak moral untuk menindas secara etnis. Foto/Ilustrasi: al Jazeera
Profesor politik Arab modern dan sejarah di Universitas Columbia, New York , Joseph Massad, mengatakan serangan Hamas ke Israel 7 Oktober 2023 lalu mengubur mitos bahwa Israel tidak akan pernah berhasil diserang secara militer.
Dia menyebut kengerian yang dirasakan Israel dan negara-negara Barat yang mendukungnya sejatinya berasal dari penghinaan rasis mereka terhadap penduduk asli Palestina .
"Perasaan terhina di Barat bahwa bangsa non-Eropa yang terjajah dan inferior secara ras dapat melawan dan mengalahkan penjajah mereka bukanlah hal yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah kolonial," tulis Joseph Massad dalam artikelnya berjudul "How Israel's genocidal war against Palestinians is a colonial tradition" yang dilansir MEE, 18 Desember 2023.
Joseph Massad mencontohkan, pada akhir abad ke-19, Inggris mengalami kekalahan kolonial paling termasyhur di tangan tentara kerajaan Zulu.
Selama Pertempuran Isandlwana pada bulan Januari 1879 di Afrika bagian selatan, tentara Zulu yang bersenjata ringan berkekuatan 20.000 orang mempermalukan pasukan kolonial Inggris, meskipun persenjataan mereka lebih unggul, menewaskan 1.300 (700 di antaranya adalah orang Afrika) dari total 1.800 tentara penyerang dan 400 tentara. warga sipil. Pertempuran tersebut menyebabkan antara 1.000 dan 3.000 pasukan Zulu tewas.
Pembalasan Kolonial
Menurut Joseph Massad, kekalahan yang mengejutkan ini membuat harga diri Inggris hancur dan memicu ketakutan di pemerintahan Benjamin Disraeli bahwa kemenangan Zulu akan mendorong perlawanan masyarakat adat di seluruh wilayah Kekaisaran.
Pada bulan Juli 1879, Inggris berangkat untuk menginvasi kembali tanah Zulu dengan kekuatan yang jauh lebih besar, kali ini mengalahkan Zulu. Mereka membalas dendam dengan menghapus ibu kota mereka, Ulundi, meratakannya dengan tanah, dan menangkap serta mengasingkan raja Zulu. Secara total, 2.500 tentara Inggris (termasuk rekrutan mereka dari Afrika) dan 10.000 orang Zulu terbunuh.
Masih di Afrika bagian selatan, Cecil Rhodes, seorang raja pertambangan Inggris, mendirikan British South Africa Company pada tahun 1889. Perusahaan tersebut melanjutkan perjalanan dari Afrika Selatan ke utara untuk menaklukkan lebih banyak wilayah dan memperkenalkan penjajah Inggris.
Pada tahun 1890, 180 penjajah dan 200 polisi kompi berangkat ke Mashonaland (sekarang Zimbabwe) dari Bechuanaland (sekarang Botswana). Tahun itu, Rhodes menjadi perdana menteri Cape Colony.
Perambahan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut menghadapi perlawanan lokal yang keras dari masyarakat Shona dan Ndebele pada tahun 1893 dan 1896.
Pada tahun 1893, kebiadaban penjajah kulit putih sedemikian rupa sehingga mereka menyebut pembantaian masyarakat Ndebele sebagai “tembakan ayam hutan”.
Selama pemberontakan tahun 1896, Shona dan Ndebele membunuh 370 penjajah kulit putih, yang mendorong Inggris untuk mengirimkan 800 tentara ke koloni pemukim baru untuk memadamkan pemberontakan anti-kolonial, yang dijuluki Chimurenga (berarti “pembebasan” dalam bahasa Shona). Secara keseluruhan, 600 orang kulit putih dibunuh dari 4.000 populasi kolonial.
Respons kulit putih bahkan lebih kejam dibandingkan pembunuhan tahun 1893. Seorang penjajah kulit putih “menembak para penggembala dan mengambil telinga mereka, yang lain memotong sebagian kulit korbannya untuk membuat tambalan tembakau.”
Para penjajah membunuh orang-orang Afrika tanpa pandang bulu, menghancurkan tanaman, dan mendinamisasi rumah-rumah. Pembantaian dan penghancuran tersebut menyebabkan kelaparan yang meluas, sementara para pemimpin pemberontakan dibunuh dan mereka yang selamat diburu, diadili, dan digantung.
Demikian pula, pada tahun 1896, orang-orang Italia, yang telah mendirikan koloni pemukim di Eritrea, memutuskan, dengan dorongan Inggris, untuk menyerang Etiopia untuk memperoleh lebih banyak tanah, hanya untuk dipermalukan dan dikalahkan oleh tentara Kaisar Menelik II dari Etiopia yang bersenjata Prancis. Ribuan tentara Etiopia, Eritrea, dan Italia tewas dalam Pertempuran Adwa.
Kekalahan tentara Eropa oleh tentara Afrika membuat Italia dipermalukan di hadapan rekan-rekannya di Eropa dan berusaha membalas dendam, yang harus menunggu datangnya pemerintahan fasis. Mussolini-lah yang membalas kekalahan di Adwa ketika ia menginvasi Etiopia pada tahun 1935. Kali ini, Italia membunuh 70.000 orang Etiopia dan mengubah Etiopia menjadi koloni pemukim.
Di sebelah utara lagi, tentara pemimpin Sudan Muhammad Ahmad bin Abdullah, yang dikenal sebagai al-Mahdi, menaklukkan Khartoum dari penjajah Inggris dan mengalahkan pasukan mereka pada Januari 1885. Al-Mahdi meninggal pada Agustus 1885 karena tifus.
Mengingat keprihatinan mereka atas kekalahan Italia di Adwa, Inggris menaklukkan kembali Sudan pada tahun 1896 dan merebut Khartoum pada tahun 1898 setelah membunuh 12.000 orang Sudan dengan artileri dan senapan mesin, melukai dan menangkap lebih dari 15.000 orang. Inggris kehilangan 700 orang, termasuk tentara Mesir dan Sudan yang merupakan bagian dari pasukan Inggris.
Bahkan jika mereka mati, para pemimpin pribumi akan tetap menjadi sasaran praktik pemenggalan kepala yang dilakukan oleh kolonial Eropa. Penakluk Inggris Lord Kitchener memerintahkan penggalian jenazah al-Mahdi, memenggalnya, melemparkan jenazahnya ke sungai Nil, dan berpikir untuk menggunakan tengkorak itu sebagai wadah tinta jika bukan karena instruksi yang datang dari Ratu Victoria setelah mendengar kekejian tersebut.
Balas Dendam Israel
Preseden kolonial ini merupakan hal mendasar dalam mempertimbangkan rasa dendam negara-negara kulit putih di Barat ketika mereka dipermalukan secara militer oleh “masyarakat kecil” yang menolak penaklukan kolonial mereka.
Pada tahun 1954, setelah Prancis menderita kekalahan telak di Dien Bien Phu di Vietnam utara, Amerika segera mengambil alih peran perang, menewaskan jutaan orang dalam dua dekade berikutnya di seluruh Asia Tenggara.
Setelah dipermalukan pada tanggal 7 Oktober di tangan para pejuang pimpinan Hamas, yang terus mencetak kemenangan militer besar melawan pasukan penyerang di Gaza, pembalasan Israel dilanjutkan dengan melancarkan perang genosida habis-habisan terhadap warga Palestina. Serangan yang sedang berlangsung ini didukung secara logistik dan finansial oleh negara-negara supremasi kulit putih di Eropa dan AS, yang juga memberikan perlindungan politik dan moral.
Pers Eropa dan AS telah memainkan peran aktif dalam mempromosikan pembenaran atas genosida Israel terhadap rakyat Palestina melalui promosi cerita-cerita rasis tentang kekerasan barbar dan primitif di Palestina, yang banyak di antaranya telah dibantah dan ditarik kembali. Namun pemalsuan rasis ini terus dianggap benar oleh para pemimpin politik barat.
Konsensus Barat mengenai perlunya melakukan genosida terhadap rakyat Palestina secara akurat dirangkum oleh Presiden Israel Isaac Herzog yang menyatakan bahwa perang genosida supremasi Yahudi Israel “bukan hanya antara Israel dan Hamas. Ini adalah perang yang benar-benar dimaksudkan untuk menyelamatkan peradaban barat, untuk menyelamatkan nilai-nilai peradaban barat.”
Dia menambahkan, sebagai penghormatan terhadap penggunaan moralitas Kristen oleh Ronald Reagan dalam kampanyenya untuk menjatuhkan Uni Soviet, bahwa musuh Israel tidak lain adalah “kerajaan kejahatan”. Untuk menjelaskan mengapa konsensus luas Eropa dan Amerika Serikat mendukung “pemusnahan” Gaza dan rakyatnya, Herzog berpendapat bahwa “jika bukan karena kita, Eropa akan menjadi sasaran berikutnya, dan Amerika Serikat akan menyusul.”
Pembelaan seperti itu merupakan ciri khas pemukim kolonial Eropa yang menganut supremasi kulit putih.
Pada tahun 1965, dua bulan sebelum pemukim kulit putih Rhodesia mendeklarasikan kemerdekaan, Brigadir Andrew Skeen, komisaris tinggi terakhir Rhodesia di London, membela supremasi kulit putih dan kolonialisme pemukim di Rhodesia dengan menyatakan bahwa “invasi Timur ke Barat dapat dihentikan dan diputarbalikkan,” dan karena nasib Rhodesia “dipertaruhkan”, hal ini “mengarah pada momen ketika Rhodesia mengambil peran sebagai pelopor peradaban barat.”
Berbeda dengan pemukim kolonial Kristen kulit putih yang sering menggunakan superioritas rasial dan membela peradaban Barat untuk membenarkan kejahatan genosida mereka, Israel juga menggunakan supremasi Yahudi dan peradaban Barat untuk membenarkan kejahatan genosida mereka.
Namun, pemerintah Israel dan pendukung Zionisnya mempunyai satu pembenaran yang lebih kuat, yang tidak dapat dilakukan oleh para pemukim kolonial Kristen kulit putih, yaitu seruan Holocaust dan sejarah antisemitisme yang, klaim Israel, memberikan mereka hak moral untuk menindas secara etnis.
Pembelaan Israel yang selalu terbuka dan rebarbatif terhadap kejahatan genosida adalah klaimnya bahwa karena kaum Yahudi Eropa menjadi sasaran genosida yang dilakukan oleh warga Kristen kulit putih Eropa, maka pemerintah Israel dapat melakukan, atas nama kaum Yahudi, kekejaman apa pun yang dianggap perlu terhadap rakyat Palestina. - bahkan jika itu berarti melibas dan mengubur hidup-hidup puluhan warga sipil.
Siapa pun yang berani mempertanyakan genosida mulia Israel terhadap warga Palestina dalam membela peradaban Barat, seperti yang mungkin dilakukan Pengadilan Kriminal Internasional jika mereka menyelidiki kejahatan Israel, berarti mereka mempraktikkan “antisemitisme murni”, seperti yang diproklamirkan Benjamin Netanyahu dengan penuh keangkuhan.
Warisan Kolonial
Mengingat sejarah kekejaman Israel yang mengerikan terhadap warga Palestina, terutama mereka yang berada di kamp konsentrasi Gaza yang telah mengalami manifestasi paling kejam selama hampir dua dekade, banyak komentator yang memberikan berbagai analogi untuk mengutuk atau menjelaskan apa yang terjadi pada tanggal 7 Oktober.
Dalam wawancara baru-baru ini dengan The New Yorker, sejarawan Palestina-Amerika Rashid Khalidi, yang menjabat sebagai penasihat Organisasi Pembebasan Palestina di Madrid dan Washington pada awal tahun 1990an tentang cara menegosiasikan apa yang disebut “proses perdamaian” di Kissingerian, mengutuk perlawanan Palestina: “Jika gerakan pembebasan penduduk asli Amerika datang dan melancarkan R.P.G. di gedung apartemenku karena aku tinggal di tanah curian, apakah itu bisa dibenarkan?”
Dia menegaskan: “Tentu saja hal itu tidak bisa dibenarkan… Anda bisa menerima hukum humaniter internasional atau tidak.”
Namun analogi Khalidi yang menuai kritik terhadap X ternyata keliru. Seandainya warga Palestina yang terjajah di Israel membom orang-orang Yahudi Israel yang kini tinggal di tanah curian mereka, analogi dengan penduduk asli Amerika mungkin ada gunanya.
Meski begitu, hal ini akan mengingatkan kembali pada representasi penduduk asli Amerika yang rasis dalam “Deklarasi Kemerdekaan” AS sebagai “orang-orang Indian Savage yang kejam dan dikenal dengan aturan peperangan yang menghancurkan segala usia, jenis kelamin, dan kondisi, seperti yang dibalas oleh sarjana dan aktivis Nick Estes dari organisasi penduduk asli Amerika, Red Nation.
Dengan analogi yang berbeda, sejarawan Yahudi Amerika Norman Finkelstein, yang orang tuanya adalah penyintas kamp konsentrasi, menyamakan perlawanan Palestina dengan narapidana Yahudi yang keluar dari kamp konsentrasi dan “mendobrak gerbang”. Ia menambahkan, ibunya sendiri mendukung pemboman tanpa pandang bulu terhadap warga sipil Jerman di Dresden. Banyak analogi lain termasuk revolusi Haiti dan pemberontakan budak Nat Turner.
Sementara itu, tidak ada seorang pun yang dapat memberikan analogi mengenai dukungan besar-besaran yang diberikan masyarakat Israel terhadap pemusnahan warga Palestina di Gaza. Menurut jajak pendapat Institut Demokrasi Israel dan Indeks Perdamaian Universitas Tel Aviv yang diambil lebih dari sebulan setelah dimulainya pemboman besar-besaran Israel di Gaza yang saat itu telah menewaskan ribuan orang, “57,5 persen warga Yahudi Israel mengatakan bahwa mereka yakin IDF juga memanfaatkan hal tersebut. hanya ada sedikit senjata di Gaza, 36,6 persen mengatakan IDF menggunakan jumlah senjata yang sesuai, sementara hanya 1,8 persen yang mengatakan mereka yakin IDF menggunakan terlalu banyak senjata.”
Namun, dibandingkan menggunakan analogi nyata atau fiksi, perlawanan Palestina terhadap kolonialisme pemukim Israel harus selalu ditempatkan dalam sejarah perjuangan anti-kolonial yang mendahuluinya. Kemarahan rasis yang baru-baru ini terjadi di Barat dan perang genosida Israel terhadap warga Palestina yang ditawan merupakan kelanjutan dari garis keturunan kolonial ini.
Warga Etiopia, Zulus, Sudan, dan Zimbabwe adalah beberapa dari mereka yang kehilangan puluhan ribu jiwa akibat supremasi kulit putih dan kolonialisme pemukim. Penduduk asli Aljazair, Tunisia, Mozambik, Angola, dan Afrika Selatan, apalagi Vietnam, Kamboja, dan Laos, juga telah kehilangan jutaan dolar dalam perjuangan mereka antara tahun 1954 dan 1994.
Selama 140 tahun terakhir, dan lebih dramatis lagi dalam 75 tahun terakhir, penduduk asli Palestina juga telah menjadi korban dari warisan kolonialisme pemukim Eropa yang didasarkan pada supremasi Yahudi dan pembelaan “peradaban barat”.
Dia menyebut kengerian yang dirasakan Israel dan negara-negara Barat yang mendukungnya sejatinya berasal dari penghinaan rasis mereka terhadap penduduk asli Palestina .
"Perasaan terhina di Barat bahwa bangsa non-Eropa yang terjajah dan inferior secara ras dapat melawan dan mengalahkan penjajah mereka bukanlah hal yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah kolonial," tulis Joseph Massad dalam artikelnya berjudul "How Israel's genocidal war against Palestinians is a colonial tradition" yang dilansir MEE, 18 Desember 2023.
Joseph Massad mencontohkan, pada akhir abad ke-19, Inggris mengalami kekalahan kolonial paling termasyhur di tangan tentara kerajaan Zulu.
Selama Pertempuran Isandlwana pada bulan Januari 1879 di Afrika bagian selatan, tentara Zulu yang bersenjata ringan berkekuatan 20.000 orang mempermalukan pasukan kolonial Inggris, meskipun persenjataan mereka lebih unggul, menewaskan 1.300 (700 di antaranya adalah orang Afrika) dari total 1.800 tentara penyerang dan 400 tentara. warga sipil. Pertempuran tersebut menyebabkan antara 1.000 dan 3.000 pasukan Zulu tewas.
Pembalasan Kolonial
Menurut Joseph Massad, kekalahan yang mengejutkan ini membuat harga diri Inggris hancur dan memicu ketakutan di pemerintahan Benjamin Disraeli bahwa kemenangan Zulu akan mendorong perlawanan masyarakat adat di seluruh wilayah Kekaisaran.
Pada bulan Juli 1879, Inggris berangkat untuk menginvasi kembali tanah Zulu dengan kekuatan yang jauh lebih besar, kali ini mengalahkan Zulu. Mereka membalas dendam dengan menghapus ibu kota mereka, Ulundi, meratakannya dengan tanah, dan menangkap serta mengasingkan raja Zulu. Secara total, 2.500 tentara Inggris (termasuk rekrutan mereka dari Afrika) dan 10.000 orang Zulu terbunuh.
Masih di Afrika bagian selatan, Cecil Rhodes, seorang raja pertambangan Inggris, mendirikan British South Africa Company pada tahun 1889. Perusahaan tersebut melanjutkan perjalanan dari Afrika Selatan ke utara untuk menaklukkan lebih banyak wilayah dan memperkenalkan penjajah Inggris.
Pada tahun 1890, 180 penjajah dan 200 polisi kompi berangkat ke Mashonaland (sekarang Zimbabwe) dari Bechuanaland (sekarang Botswana). Tahun itu, Rhodes menjadi perdana menteri Cape Colony.
Perambahan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut menghadapi perlawanan lokal yang keras dari masyarakat Shona dan Ndebele pada tahun 1893 dan 1896.
Pada tahun 1893, kebiadaban penjajah kulit putih sedemikian rupa sehingga mereka menyebut pembantaian masyarakat Ndebele sebagai “tembakan ayam hutan”.
Selama pemberontakan tahun 1896, Shona dan Ndebele membunuh 370 penjajah kulit putih, yang mendorong Inggris untuk mengirimkan 800 tentara ke koloni pemukim baru untuk memadamkan pemberontakan anti-kolonial, yang dijuluki Chimurenga (berarti “pembebasan” dalam bahasa Shona). Secara keseluruhan, 600 orang kulit putih dibunuh dari 4.000 populasi kolonial.
Respons kulit putih bahkan lebih kejam dibandingkan pembunuhan tahun 1893. Seorang penjajah kulit putih “menembak para penggembala dan mengambil telinga mereka, yang lain memotong sebagian kulit korbannya untuk membuat tambalan tembakau.”
Para penjajah membunuh orang-orang Afrika tanpa pandang bulu, menghancurkan tanaman, dan mendinamisasi rumah-rumah. Pembantaian dan penghancuran tersebut menyebabkan kelaparan yang meluas, sementara para pemimpin pemberontakan dibunuh dan mereka yang selamat diburu, diadili, dan digantung.
Demikian pula, pada tahun 1896, orang-orang Italia, yang telah mendirikan koloni pemukim di Eritrea, memutuskan, dengan dorongan Inggris, untuk menyerang Etiopia untuk memperoleh lebih banyak tanah, hanya untuk dipermalukan dan dikalahkan oleh tentara Kaisar Menelik II dari Etiopia yang bersenjata Prancis. Ribuan tentara Etiopia, Eritrea, dan Italia tewas dalam Pertempuran Adwa.
Kekalahan tentara Eropa oleh tentara Afrika membuat Italia dipermalukan di hadapan rekan-rekannya di Eropa dan berusaha membalas dendam, yang harus menunggu datangnya pemerintahan fasis. Mussolini-lah yang membalas kekalahan di Adwa ketika ia menginvasi Etiopia pada tahun 1935. Kali ini, Italia membunuh 70.000 orang Etiopia dan mengubah Etiopia menjadi koloni pemukim.
Di sebelah utara lagi, tentara pemimpin Sudan Muhammad Ahmad bin Abdullah, yang dikenal sebagai al-Mahdi, menaklukkan Khartoum dari penjajah Inggris dan mengalahkan pasukan mereka pada Januari 1885. Al-Mahdi meninggal pada Agustus 1885 karena tifus.
Mengingat keprihatinan mereka atas kekalahan Italia di Adwa, Inggris menaklukkan kembali Sudan pada tahun 1896 dan merebut Khartoum pada tahun 1898 setelah membunuh 12.000 orang Sudan dengan artileri dan senapan mesin, melukai dan menangkap lebih dari 15.000 orang. Inggris kehilangan 700 orang, termasuk tentara Mesir dan Sudan yang merupakan bagian dari pasukan Inggris.
Bahkan jika mereka mati, para pemimpin pribumi akan tetap menjadi sasaran praktik pemenggalan kepala yang dilakukan oleh kolonial Eropa. Penakluk Inggris Lord Kitchener memerintahkan penggalian jenazah al-Mahdi, memenggalnya, melemparkan jenazahnya ke sungai Nil, dan berpikir untuk menggunakan tengkorak itu sebagai wadah tinta jika bukan karena instruksi yang datang dari Ratu Victoria setelah mendengar kekejian tersebut.
Balas Dendam Israel
Preseden kolonial ini merupakan hal mendasar dalam mempertimbangkan rasa dendam negara-negara kulit putih di Barat ketika mereka dipermalukan secara militer oleh “masyarakat kecil” yang menolak penaklukan kolonial mereka.
Pada tahun 1954, setelah Prancis menderita kekalahan telak di Dien Bien Phu di Vietnam utara, Amerika segera mengambil alih peran perang, menewaskan jutaan orang dalam dua dekade berikutnya di seluruh Asia Tenggara.
Setelah dipermalukan pada tanggal 7 Oktober di tangan para pejuang pimpinan Hamas, yang terus mencetak kemenangan militer besar melawan pasukan penyerang di Gaza, pembalasan Israel dilanjutkan dengan melancarkan perang genosida habis-habisan terhadap warga Palestina. Serangan yang sedang berlangsung ini didukung secara logistik dan finansial oleh negara-negara supremasi kulit putih di Eropa dan AS, yang juga memberikan perlindungan politik dan moral.
Pers Eropa dan AS telah memainkan peran aktif dalam mempromosikan pembenaran atas genosida Israel terhadap rakyat Palestina melalui promosi cerita-cerita rasis tentang kekerasan barbar dan primitif di Palestina, yang banyak di antaranya telah dibantah dan ditarik kembali. Namun pemalsuan rasis ini terus dianggap benar oleh para pemimpin politik barat.
Konsensus Barat mengenai perlunya melakukan genosida terhadap rakyat Palestina secara akurat dirangkum oleh Presiden Israel Isaac Herzog yang menyatakan bahwa perang genosida supremasi Yahudi Israel “bukan hanya antara Israel dan Hamas. Ini adalah perang yang benar-benar dimaksudkan untuk menyelamatkan peradaban barat, untuk menyelamatkan nilai-nilai peradaban barat.”
Dia menambahkan, sebagai penghormatan terhadap penggunaan moralitas Kristen oleh Ronald Reagan dalam kampanyenya untuk menjatuhkan Uni Soviet, bahwa musuh Israel tidak lain adalah “kerajaan kejahatan”. Untuk menjelaskan mengapa konsensus luas Eropa dan Amerika Serikat mendukung “pemusnahan” Gaza dan rakyatnya, Herzog berpendapat bahwa “jika bukan karena kita, Eropa akan menjadi sasaran berikutnya, dan Amerika Serikat akan menyusul.”
Pembelaan seperti itu merupakan ciri khas pemukim kolonial Eropa yang menganut supremasi kulit putih.
Pada tahun 1965, dua bulan sebelum pemukim kulit putih Rhodesia mendeklarasikan kemerdekaan, Brigadir Andrew Skeen, komisaris tinggi terakhir Rhodesia di London, membela supremasi kulit putih dan kolonialisme pemukim di Rhodesia dengan menyatakan bahwa “invasi Timur ke Barat dapat dihentikan dan diputarbalikkan,” dan karena nasib Rhodesia “dipertaruhkan”, hal ini “mengarah pada momen ketika Rhodesia mengambil peran sebagai pelopor peradaban barat.”
Berbeda dengan pemukim kolonial Kristen kulit putih yang sering menggunakan superioritas rasial dan membela peradaban Barat untuk membenarkan kejahatan genosida mereka, Israel juga menggunakan supremasi Yahudi dan peradaban Barat untuk membenarkan kejahatan genosida mereka.
Namun, pemerintah Israel dan pendukung Zionisnya mempunyai satu pembenaran yang lebih kuat, yang tidak dapat dilakukan oleh para pemukim kolonial Kristen kulit putih, yaitu seruan Holocaust dan sejarah antisemitisme yang, klaim Israel, memberikan mereka hak moral untuk menindas secara etnis.
Pembelaan Israel yang selalu terbuka dan rebarbatif terhadap kejahatan genosida adalah klaimnya bahwa karena kaum Yahudi Eropa menjadi sasaran genosida yang dilakukan oleh warga Kristen kulit putih Eropa, maka pemerintah Israel dapat melakukan, atas nama kaum Yahudi, kekejaman apa pun yang dianggap perlu terhadap rakyat Palestina. - bahkan jika itu berarti melibas dan mengubur hidup-hidup puluhan warga sipil.
Siapa pun yang berani mempertanyakan genosida mulia Israel terhadap warga Palestina dalam membela peradaban Barat, seperti yang mungkin dilakukan Pengadilan Kriminal Internasional jika mereka menyelidiki kejahatan Israel, berarti mereka mempraktikkan “antisemitisme murni”, seperti yang diproklamirkan Benjamin Netanyahu dengan penuh keangkuhan.
Warisan Kolonial
Mengingat sejarah kekejaman Israel yang mengerikan terhadap warga Palestina, terutama mereka yang berada di kamp konsentrasi Gaza yang telah mengalami manifestasi paling kejam selama hampir dua dekade, banyak komentator yang memberikan berbagai analogi untuk mengutuk atau menjelaskan apa yang terjadi pada tanggal 7 Oktober.
Dalam wawancara baru-baru ini dengan The New Yorker, sejarawan Palestina-Amerika Rashid Khalidi, yang menjabat sebagai penasihat Organisasi Pembebasan Palestina di Madrid dan Washington pada awal tahun 1990an tentang cara menegosiasikan apa yang disebut “proses perdamaian” di Kissingerian, mengutuk perlawanan Palestina: “Jika gerakan pembebasan penduduk asli Amerika datang dan melancarkan R.P.G. di gedung apartemenku karena aku tinggal di tanah curian, apakah itu bisa dibenarkan?”
Dia menegaskan: “Tentu saja hal itu tidak bisa dibenarkan… Anda bisa menerima hukum humaniter internasional atau tidak.”
Namun analogi Khalidi yang menuai kritik terhadap X ternyata keliru. Seandainya warga Palestina yang terjajah di Israel membom orang-orang Yahudi Israel yang kini tinggal di tanah curian mereka, analogi dengan penduduk asli Amerika mungkin ada gunanya.
Meski begitu, hal ini akan mengingatkan kembali pada representasi penduduk asli Amerika yang rasis dalam “Deklarasi Kemerdekaan” AS sebagai “orang-orang Indian Savage yang kejam dan dikenal dengan aturan peperangan yang menghancurkan segala usia, jenis kelamin, dan kondisi, seperti yang dibalas oleh sarjana dan aktivis Nick Estes dari organisasi penduduk asli Amerika, Red Nation.
Dengan analogi yang berbeda, sejarawan Yahudi Amerika Norman Finkelstein, yang orang tuanya adalah penyintas kamp konsentrasi, menyamakan perlawanan Palestina dengan narapidana Yahudi yang keluar dari kamp konsentrasi dan “mendobrak gerbang”. Ia menambahkan, ibunya sendiri mendukung pemboman tanpa pandang bulu terhadap warga sipil Jerman di Dresden. Banyak analogi lain termasuk revolusi Haiti dan pemberontakan budak Nat Turner.
Sementara itu, tidak ada seorang pun yang dapat memberikan analogi mengenai dukungan besar-besaran yang diberikan masyarakat Israel terhadap pemusnahan warga Palestina di Gaza. Menurut jajak pendapat Institut Demokrasi Israel dan Indeks Perdamaian Universitas Tel Aviv yang diambil lebih dari sebulan setelah dimulainya pemboman besar-besaran Israel di Gaza yang saat itu telah menewaskan ribuan orang, “57,5 persen warga Yahudi Israel mengatakan bahwa mereka yakin IDF juga memanfaatkan hal tersebut. hanya ada sedikit senjata di Gaza, 36,6 persen mengatakan IDF menggunakan jumlah senjata yang sesuai, sementara hanya 1,8 persen yang mengatakan mereka yakin IDF menggunakan terlalu banyak senjata.”
Namun, dibandingkan menggunakan analogi nyata atau fiksi, perlawanan Palestina terhadap kolonialisme pemukim Israel harus selalu ditempatkan dalam sejarah perjuangan anti-kolonial yang mendahuluinya. Kemarahan rasis yang baru-baru ini terjadi di Barat dan perang genosida Israel terhadap warga Palestina yang ditawan merupakan kelanjutan dari garis keturunan kolonial ini.
Warga Etiopia, Zulus, Sudan, dan Zimbabwe adalah beberapa dari mereka yang kehilangan puluhan ribu jiwa akibat supremasi kulit putih dan kolonialisme pemukim. Penduduk asli Aljazair, Tunisia, Mozambik, Angola, dan Afrika Selatan, apalagi Vietnam, Kamboja, dan Laos, juga telah kehilangan jutaan dolar dalam perjuangan mereka antara tahun 1954 dan 1994.
Selama 140 tahun terakhir, dan lebih dramatis lagi dalam 75 tahun terakhir, penduduk asli Palestina juga telah menjadi korban dari warisan kolonialisme pemukim Eropa yang didasarkan pada supremasi Yahudi dan pembelaan “peradaban barat”.
(mhy)
Lihat Juga :